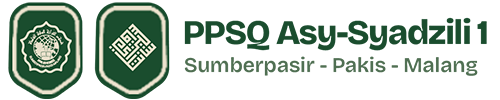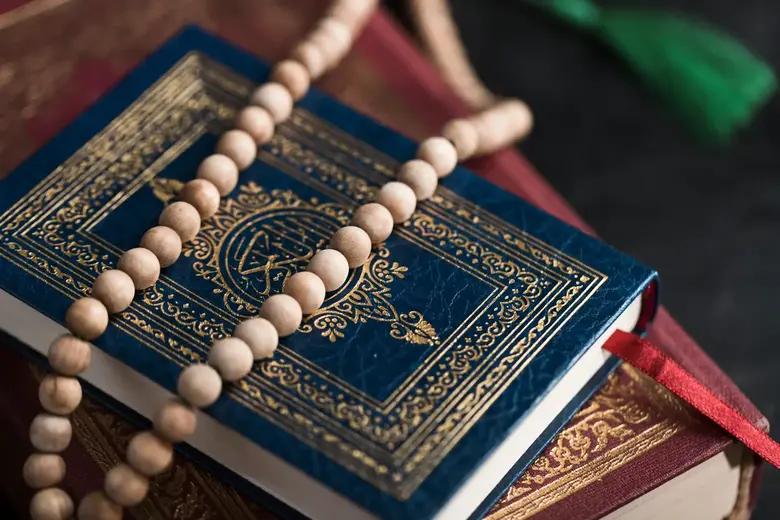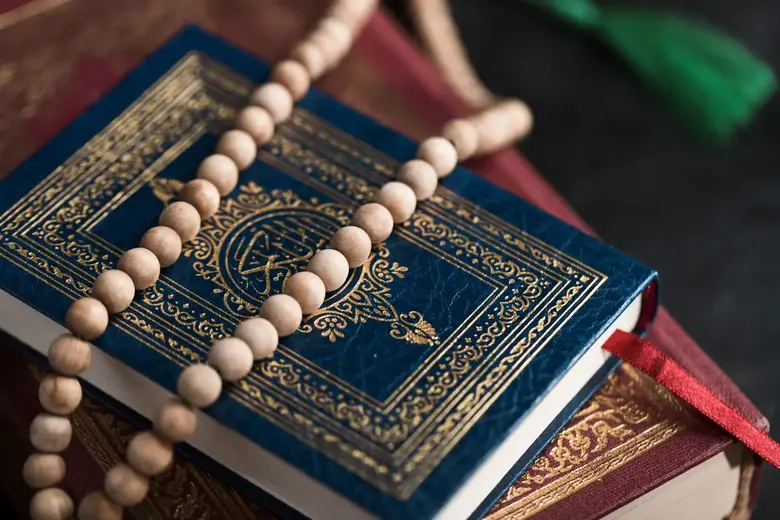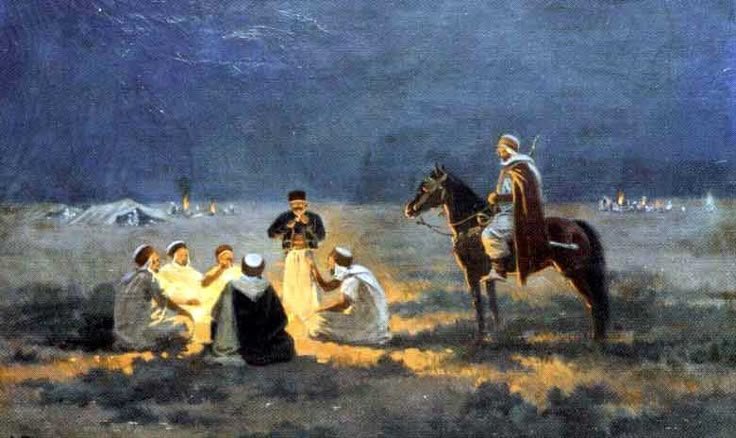AL-QUR'AN DITURUNKAN DENGAN TUJUH HURUF
Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa beberapa macam bacaan sangat penting karena berhubungan langsung dengan kitab paling mulia yang berada didepan kaum muslimin, yaitu kitabullah. Pada hakikatnya seorang muslim tidak akan menolak dan tidak pula ragu sedikitpun untuk menyatakan bahwa macam-macam bacaan di Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, bukan semata-mata berdasarkan pendapat para sahabat atau hasil ijtihad para Imam Qiro'at. Keberadaan beberapa macam bacaan Al-Qur'an merupakan penjabaran dari tujuh huruf sebagaimana ditegaskan oleh abda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadits:
اِنَّ هَذَا اْلقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٌ أَحْرُفٍ فَاقْرَأُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)
“Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan tujuh huruf, maka dibacalah olehmu apa yang dirasakan mudah dan nyaman.” (HR Bukhari Muslim)
Angka tujuh atau sab'ah ( سَبْعَةٌ ) terkadang dipakai dalam pengertian majaz yang mengungkapkan jumlah yang banyak, akan tetapi yang dimaksud dalam hadits adalah jumlah bilangan di atas enam dan di bawah delapan. Sedangkan kata ahruf ( أَحْرُفٍ ) dalam hadits adalah jama' dari harf ( حَرْفً ). Harf artinya satu ujung atau satu sisi dari sesuatu atau sesuatu yang terdengar ketika melafadhkan salah satu huruf hija'iyah seperti halnya harf di dalam firman Allah SWT pada surat Al-Hajj yang bermakna wajh (cara) sebagai berikut:
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ (الحج: 11)
“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi (harf).” (Al-Hajj: 11)
Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian manusia beribadah kepada Allah tidak dengan penuh keyakinan atau pada saat senang (satu sisi kehidupan), tidak pada saat susah (satu sisi kehidupan lainnya). Setiap kata yang dibaca dengan satu wajah (cara) dari Al-Qur'an disebut harf. Kata harf juga bisa berarti bahasa seperti dalam istilah حَرِفُ قُرَيشٍ (harfu Quraisy) yang berarti bahasa Quraisy dan sebagianya dari sekian banyak arti harf yang dimilikinya.
Banyak pendapat ulama' tentang maksud dari tujuh huruf ( sab'ati ahruf ). Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh bahasa yang ada di masyarakat Arab yaitu Quraisy, Hudzail, Tsaqif, Hawazin, Tamim, Qinanah dan Yaman. Adapula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah nilai-nilai hukum seperti halal, haram, muhkam, mutasyabih, amtsal, insya dan ikhbar. Adapun pendapat yang diperkuat oleh para ulama' adalah madzhab Imam Arrozi (W. 606 H) yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah cara-cara bacaan yang berbeda yang tidak keluar dari tujuh sisi. Perbedaan tujuh sisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Perbedaan ragam kata benda baik mufrad, tasniyah, jama' mudzakkar dan mu'annats, seperti pada firman-Nya
وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة :184)
Ayat 184 di atas yang membaca dengan mufrad (مِسْكِينٍ), adapula yang membaca dengan jama’ (مَسَاكِينَ).
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ (الحجرات: 10)
Ayat 10 di atas ada yang membaca dengan tatsniyah (اَخَوَيْكُمْ), adapula yang membaca dengan jama’ (اِخْوَتِكُمْ).
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ (البقرة: 48)
Ayat 48 di atas ada yang membaca dengan mudzakkar (وَلَا يُقْبَلُ), adapula yang membaca dengan mu’annats (وَلَاتُقْبَلُ).
2. Perbedaan tashrif (perubahan arakat dan bentuk kalimat) beberapa fi’il, dari fi’il madhi ke mudhari’ dan ke amr seperti pada firman-Nya:
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ (البقرة: 184)
Ayat 184 di atas ada yang membaca dalam bentuk fi’il madhi (تَطَوَّعَ), adapula yang membaca dalam bentuk fi’il mudhari’ yang sukun huruf ainnya (يَطَوَّعْ) karna sebelumnya ada man pada فَمَن.
قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِۖ (الأ نبيا: 4)
Ayat 4 di atas ada yang membaca dalam bentuk fi’il madhi (قٰلَ رَبِّيْ), adapula yang membaca dalam bentuk fi’il amr (قُلْ رَبِّيْ).
3. Perbedaan cara-cara i’rab (perubahan harakat atau bentuk kalimat) seperti pada firman-Nya:
وَّلَا تُسۡـَٔـلُ عَنۡ اَصۡحٰبِ الۡجَحِيۡمِ (البقرة: 119)
Ayat 119 di atas adfa yang membaca ta’ dan lam berharakat dlommah (وَّلَا تُسۡـَٔـلُ) kerna huruf لا posisinya sebagai لا nafiyah, adapula yang membqaca ta’ berharakat fathah sedangkan lam berharakat sukun (وَّلَا تَسۡـَٔـلْ) karena huruf لا posisinya sebagai لا nahiyah.
4. Perbedaan kurang dan lebihnya huruf seperti pada firman-Nya:
وَسَارِعُوۡۤا اِلٰى مَغۡفِرَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ (ال عمران: 133)
Jumhur atau mayoritas Imam Qiro’at membaca ayat di atas dengan menyertakan huruf wawu (وَسَارِعُوۡۤا), sedangkan imam nafi’ dan Ibnu ‘Amir membacanya dengan tanpa menyertakan huruf wawu (سَارِعُوۡۤا).
5. Perbedaan tentang susunan dua kalimat yang lebih didahulukan antara keduanya seperti pada firman-Nya:
وَقٰتَلُوۡا وَقُتِلُوۡا لَاُكَفِّرَنَّ (ال عمران: 195)
Ayat 195 di atas ada yang mendahulukan kalimat وَقٰتَلُوۡ dari pada kalimat وَقُتِلُوۡا yaitu dibaca ( وَقٰتَلُوۡا وَقُتِلُوۡا ), adapula yang lebih mendahulukan kalimat وَقُتِلُوۡا daripada kalimat وَقٰتَلُوۡ yaitu dibaca dengan وقا ( وَقُتِلُوۡا وَقاتَلُوۡ ).
6. Perbedaan tentang pergantian dan penempatan huruf, yaitu menempatkan satu huruf pada tempat huruf yang lain seperti pada firman-Nya:
هُنَالِكَ تَبۡلُوۡا كُلُّ نَفۡسٍ مَّاۤ اَسۡلَفَتۡ (يونس: 30)
Ayat 30 di atas ada yang membaca dengan ta' dan ba' ( تَبۡلُوۡا ) yang berarti menguji, adapula yang membaca dengan dua ta' ( تَتۡلُوۡا ) yang berarti membaca.
7. Perbedaan tentang dialek seperti fathah, imalah, idzhar, idgham, tashil, tahqiq, dan tafkhim. Termasuk juga perbedaaan bebrapa kalimat yang terjadi di kalangan beberapa kabilah (marga) seperti بيوت , ada yang membaca huruf ba' berharakat dlommah ( بُيٌوت ) dan adapula yang membaca ba' berharakat kasrah ( بِيُوت ).
Uraian di atas merupakan makna dari tujuh sisi, sehingga semua qiro'at tidak keluar darinya. Alasan yang memperkuat madzhab ini karena perbedaan di atas banyak ditemukan di dalam ilmu qiro'at dan merupakan hasil pengamatan yang cermat bahwa perbedaan yang terjadi dalam semua qiro'at kembali kepada tujuh sisi atau tujuh cara seperti yang dimaksudkan oleh hadits riwayat Bukhari dan Musli di atas.
*Adhiyah Qabil Nashir. Op. Cit. Hal 11-14.
Postingan Terbaru

Sesudah kesulitan ada kemudahan.
Jun 16, 2025
7 Golongan yang selamat dari mahsyar
Jun 11, 2025